Tulisan ini terinspirasi dari pertanyaan salah seorang rekan guru, “Jadi kapan terakhir anak-anak diberikan kesempatan untuk menuntaskan tugasnya biar bisa Ijin Bermalam?”
Di sekolah, data sering dipandang sebatas angka: nilai ulangan, hasil ujian, atau grafik kehadiran. Namun, di balik angka-angka itu sebenarnya tersembunyi kisah yang lebih luas tentang bagaimana seorang anak belajar, berjuang, dan berkembang. Narasi berbasis data adalah upaya untuk mengubah angka-angka tersebut menjadi cerita yang hidup, penuh makna, dan manusiawi.
Bayangkan seorang siswa yang nilainya turun drastis pada satu mata pelajaran. Apakah itu berarti ia malas? Tidak mampu? Atau ada faktor lain yang memengaruhi? Dengan melihat data secara lebih mendalam, kita bisa menemukan bahwa siswa itu sebenarnya sedang beradaptasi dengan metode belajar baru, atau justru sedang menghadapi persoalan pribadi. Data hanyalah pintu masuk, bukan kesimpulan akhir.
Seperti yang ditegaskan oleh Black & Wiliam (1998) dalam penelitian klasik tentang assessment for learning, data asesmen seharusnya menjadi titik awal untuk refleksi, bukan akhir dari penilaian. Narasi berbasis data membantu guru, siswa, dan pimpinan sekolah melihat lebih dari sekadar “angka akhir”. Ia menempatkan siswa sebagai manusia utuh, bukan sekadar skor.
Menurut saya pribadi, sebagai seorang guru, ada 3 hal yang harusnya jadi pertimbangan dalam menggali cerita di dalam data:
Pertama, tidak ada indikator absolut. Satu nilai atau satu grafik tidak bisa mendefinisikan seorang anak. Data harus dibaca secara longitudinal—dari waktu ke waktu—dan dilihat dalam konteks yang lebih luas.
Kedua, mengukur yang kualitatif. Tidak semua hal penting bisa dihitung dengan angka. Motivasi, ketekunan, atau kepercayaan diri sering kali justru muncul dari catatan refleksi, hasil diskusi, atau interaksi di kelas. Guru perlu berani membaca “cerita di balik kata-kata” siswa. Sejalan dengan pandangan Patton (2015) tentang qualitative inquiry, data naratif mampu menyingkap makna terdalam yang sering terlewat jika kita hanya terpaku pada angka.
Ketiga, pelibatan siswa dalam membaca data. Saat siswa ikut menafsirkan data mereka sendiri, mereka belajar melihat diri sebagai pengendali proses belajar, bukan objek pasif yang dinilai orang lain. Dengan cara ini, data menjadi sarana refleksi bersama, bukan “vonis” sepihak.

Di SMP Al Hikmah IIBS Batu, seorang guru -yang tidak saya sebutkan namanya di sini- menggunakan aplikasi Sekolahku, sebuah Learning Management System (LMS) yang juga bisa digunakan untuk membaca tren belajar siswa. Dari laporan-laporan yang bisa diunduh, guru tersebut melihat pola yang lebih kaya: bukan hanya nilai ulangan, tetapi juga frekuensi pengerjaan (karena biasanya siswa bisa mengerjakan satu halaman berkali-kali), waktu pengerjaan tugas, interaksi di forum diskusi, hingga catatan atau form refleksi harian yang ditulis siswa.
Ia menemukan bahwa seorang siswa yang biasanya aktif mulai jarang menyelesaikan tugas tepat waktu. Dengan membaca data dari LMS, guru melihat bahwa siswa tersebut lebih sering mengerjakan tugas saat akhir pekan (yang biasanya digunakan siswa untuk me time). Data ini lalu diverifikasi melalui percakapan langsung, dan diketahui bahwa siswa sedang kesulitan mengatur jadwal antara hafalan Al-Qur’an, kegiatan ekstrakurikuler, dan tugas akademik.
Alih-alih langsung memberi vonis, guru menggunakan analisis iteratif: data awal lalu difollow up dengan dialog dengan siswa, hasil dialog dicatat di LMS (Kejadian Harian / Catatan Anekdotal) serta melakukan tindak lanjut bersama wali kelas dan guru tahfidz. Proses ini menunjukkan bagaimana LMS memperkaya data, karena memungkinkan guru tidak hanya melihat “hasil akhir”, tetapi juga “jejak proses” belajar siswa.
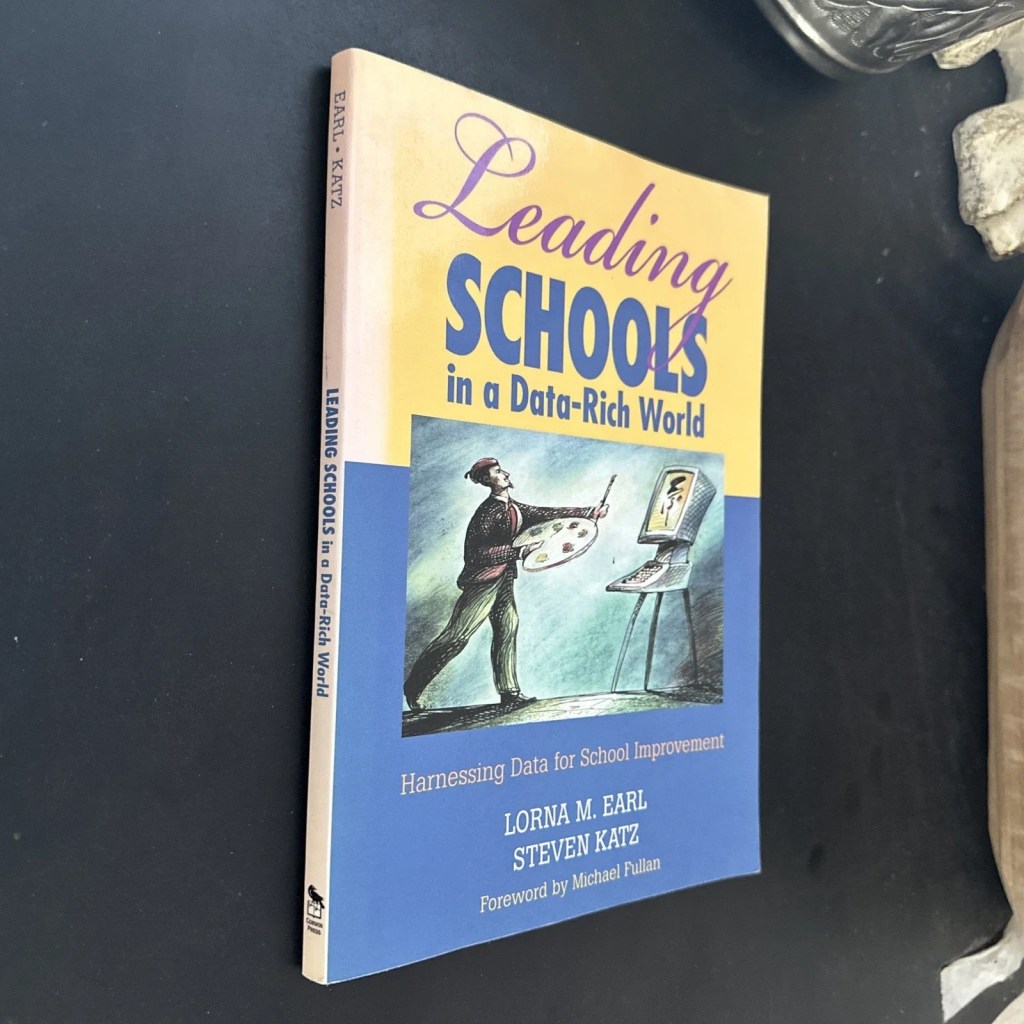
Seperti yang disebut Earl & Katz (2006), data pendidikan seharusnya dipandang sebagai percakapan berkelanjutan antara guru, siswa, dan sekolah. Saat teknologi semakin canggih dalam menunjang kebutuhan belajar, harusnya membuat percakapan itu semakin lengkap karena seluruh pihak bisa mengakses jejak belajar yang lebih utuh.
Narasi berbasis data mengajarkan kita satu hal: data bukanlah akhir, melainkan awal dari dialog. Analisisnya pun harus iteratif—dibaca, ditafsirkan, ditinjau ulang, lalu dikaitkan dengan konteks nyata siswa. Dengan adanya LMS, data siswa tidak hanya berupa angka ujian, tetapi juga potret keseharian belajar yang kaya.
Ia mengundang guru untuk mendengarkan lebih dalam, mengajak siswa untuk merefleksikan, dan mendorong sekolah untuk membuat keputusan yang lebih bijak, seperti memutuskan apakah seorang anak diberikan atau tidak diberikan hak ijin bermalam karena ia berhasil memenuhi atau tidak memenuhi target belajarnya. Dengan membangun budaya data yang sehat, sekolah tidak hanya mencetak skor tinggi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, empati, dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan konten, melainkan membantu siswa “melihat dirinya sendiri” sebagai pembelajar seutuhnya.
Referensi
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education.
- Earl, L., & Katz, S. (2006). Leading Schools in a Data-Rich World. Corwin Press.
- Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods. Sage.
Catatan Kaki: Hak Ijin Bermalam dalam konteks Al Hikmah IIBS Batu adalah hak untuk bisa liburan akhir pekan 1 bulan sekali di rumah. Untuk bisa mendapatkannya, siswa harus menuntaskan target belajar yang diberikan guru/sekolah.